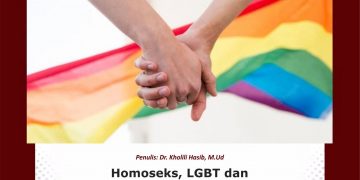Tak diragukan lagi Anda telah menyadarinya. Masih ada pria dan wanita rasional yang terlibat di media arus utama dunia Barat yang tetap membiarkan ungkapan-ungkapan yang sudah usang menghuni bahasa sehari-hari mereka ketika menulis tentang horor yang mengerikan di Gaza, seolah-olah apa yang terjadi di sana adalah sebuah “perang” umumnya sebuah konflik militer terbuka dan seringkali berkepanjangan, yang sifatnya biasa-biasa saja, antara angkatan bersenjata dari dua negara atau kelompok.
Padahal, yang sebenarnya sedang kita saksikan di sebidang tanah yang tersiksa seluas 142 mil persegi itu yang pernah digambarkan sebagai kamp penjara terbuka, namun kini sebagai kamp kematian terbuka jelas bukan perang, melainkan bencana kemanusiaan paling memilukan di abad ke-21, yang menantang rasa moralitas bersama yang melekat dalam dialog budaya global kita.
Kita tidak perlu lagi menggambarkan kengerian yang menimpa 2,3 juta jiwa yang “hidup” ya, kata ini perlu diberi tanda kutip di Gaza, sebuah rakyat yang kini diburu melampaui batas daya tahan manusia.
Kita sudah tahu kengerian itu. Kita sudah membacanya. Kita sudah menontonnya di layar kita. Dan semua itu telah mengguncang inti kemanusiaan kita.
Dua dunia
Daerah kantong yang kita sebut Gaza hari ini adalah tanah tandus yang kehancurannya berskala seperti kehancuran Kartago, di mana rakyat Palestina yang kelaparan tidak sepenuhnya mati maupun hidup. Mereka dan anak-anak mereka yang kurus kering telah digambarkan secara mengerikan sebagai “mayat berjalan.”
Anda melihat mereka di pusat-pusat distribusi makanan yang berbahaya, di mana tentara Israel yang gatal menarik pelatuk secara cuma-cuma membunuh puluhan orang setiap hari, dan di mana kemanusiaan mereka begitu tergerus menjadi serpihan sehingga mereka rela mati demi mendapatkan sebungkus beras, satu liter susu, atau jeriken air.
Namun, hanya beberapa kilometer jauhnya, di seberang perbatasan, supermarket penuh dengan makanan dan orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Berjalan di jalan-jalan mereka. Minum kopi. Menonton film. Membaca Taurat. Mengunjungi dokter gigi. Memeluk anak-anak mereka. Mendengarkan musik. Dan bercinta.
Jenazah anak-anak Palestina yang tak bernyawa adalah bukti yang menghantui tentang perang terhadap mereka yang tak berdaya, di mana bahkan yang termuda pun tidak luput (AP).
Tak diragukan lagi, ini adalah dua tatanan realitas yang keberadaannya secara spasial dan temporal bersamaan sulit direkonsiliasi oleh akal dan membuat imajinasi menciut saat membayangkannya.
Pertanyaan pun bermunculan
Apa pembenaran bagi mereka yang menolak memberi anak-anak akses pada makanan, sehingga mencegah mereka memenuhi kebutuhan paling dasar? Apa yang mendorong satu bangsa untuk secara terencana menimpakan kekejaman tak terperi secara berulang pada bangsa lain?
Dan apa yang membuat orang Israel yang tampaknya normal memberikan dukungan besar-besaran pada teriakan rasis para pemimpin politik dan militer mereka, bukannya berpaling dengan rasa muak yang tak tertahankan sehingga justru mengurangi apapun yang manusiawi di dalam diri mereka dan menghidupkan kembali sisi kebinatangan? (Fakta menyedihkan bahwa orang-orang Israel progresif selalu gagal menyisipkan, apalagi memaksakan pada masyarakat, keteguhan kemanusiaan yang melekat dalam keyakinan mereka.)
Penulis, seperti halnya orang awam lainnya, sebaiknya tidak ikut campur dalam perdebatan seperti ini yang dianggap sebagai ranah komunitas terapeutik. Namun pasti ada alasannya, meski kelam dan mengusik.
Dunia yang berpandangan sempit
Satu hal jelas. Gaza sedang terbakar. Analogi yang tepat untuknya adalah neraka. Jadi, mengapa nurani global belum memaksa para penguasa untuk turun tangan dan mengakhiri genosida di Gaza, mengakhiri penderitaan tak terukur rakyatnya? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi?
Sederhananya begini: Amerika Serikat, yang menyebut dirinya “pemimpin dunia bebas” dan “pengatur” urusan internasional, bersikeras mempertahankan dukungan lama mereka yang terkenal membabi buta terhadap Israel, benar atau salah.
Begitu besarnya dukungan itu hingga mereka berulang kali menggunakan hak veto untuk menggagalkan upaya negara-negara lain di Dewan Keamanan PBB mengakhiri kekacauan di wilayah terkepung itu.
Dan pemerintah di bagian lain dunia Barat memilih hanya menjadi penonton kekacauan itu, atau, jika tidak, menjadi pendukung diam-diamnya.
Namun, bukan berarti itu akhirnya. Nurani global itu kini telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, setelah perlahan-lahan berubah menjadi meminjam parafrasa dari pengamatan terkenal Laksamana Jepang Isoroku Yamamoto tentang serangan Jepang ke Pearl Harbour raksasa tidur yang kini terbangun dan dipenuhi tekad yang kuat.
Aksi massa, seperti di Sydney, Australia, menandai bangkitnya nurani global, penolakan kolektif untuk diam saat Gaza berdarah (AP).
Memang benar, diamnya dunia Barat dalam menghadapi horor di Gaza mungkin telah menimbulkan keraguan serius terhadap bobot nilai-nilai dasar liberalisme Barat, menampakkannya sebagai kepalsuan.
Namun, mayoritas di dunia yang sama itu kini dengan berani mengambil sikap melawan pemerintah mereka, melihatnya bukan hanya sebagai keharusan moral tetapi juga sebagai cara untuk berbicara jujur kepada kekuasaan.
Dan dengan mengambil sikap itu, mereka pada dasarnya mengatakan kepada diri mereka sendiri, satu sama lain, dan dunia secara keseluruhan bahwa manusia ikut bertanggung jawab atas sesuatu yang membuat mereka acuh tak acuh karena dengan tidak bersuara, mereka secara tidak langsung memberikan persetujuan terhadap tatanan yang berlaku.
Tak seorang pun boleh meragukan bahwa suara-suara ini telah terdengar.
Suara-suara mereka bergema lantang, jelas, dan berdampak bahkan di Amerika Serikat, yang secara tradisional merupakan jantung dukungan otomatis bagi Israel. Memang, tanda-tanda pergeseran itu sudah terlihat dalam survei publik, termasuk jajak pendapat terbaru Pew.
Ya, lebih dari 18.500 anak sejauh ini telah dibunuh oleh Israel di Gaza sebidang tanah kecil yang kini menjadi tempat di mana orang mati seakan mengulurkan tangan untuk menarik yang hidup ke dalam jurang kuburan massal, sebagai tindakan terakhir belas kasihan di tempat di mana hidup telah kehilangan makna.
Adapun kami, orang-orang Palestina yang, karena trik nasib, berada “di sini” diberi makan lebih dari cukup, aman di tempat tidur dan jalan-jalan kami, terlindung dari kekacauan dalam kehidupan sehari-hari apa yang terjadi “di sana”, di sebidang neraka itu, tetap tak terpisahkan dari identitas kami dan akan tetap tertulis dengan tinta tak terhapuskan. Ia terukir dalam ingatan kolektif kami dan akan tetap bersama kami selama beberapa generasi.
Dan buku-buku sejarah kami akan mencatat bahwa tidak ada satu pun anak yang dibantai di Gaza yang pernah dilupakan, dan tidak ada satu pun kekejaman yang dilakukan di sana yang pernah dimaafkan.
***********
Penulis: Fawaz Turki
(Author TRT World, Dosen dan Jurnalis Asal Palestina)
Demikian Semoga Bermanfaat…
@Wallahu ‘alam bishowab…
Artikel: www.mujahiddakwah.com (Mengispirasi dan Menyuarakan Kebenaran)